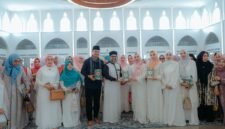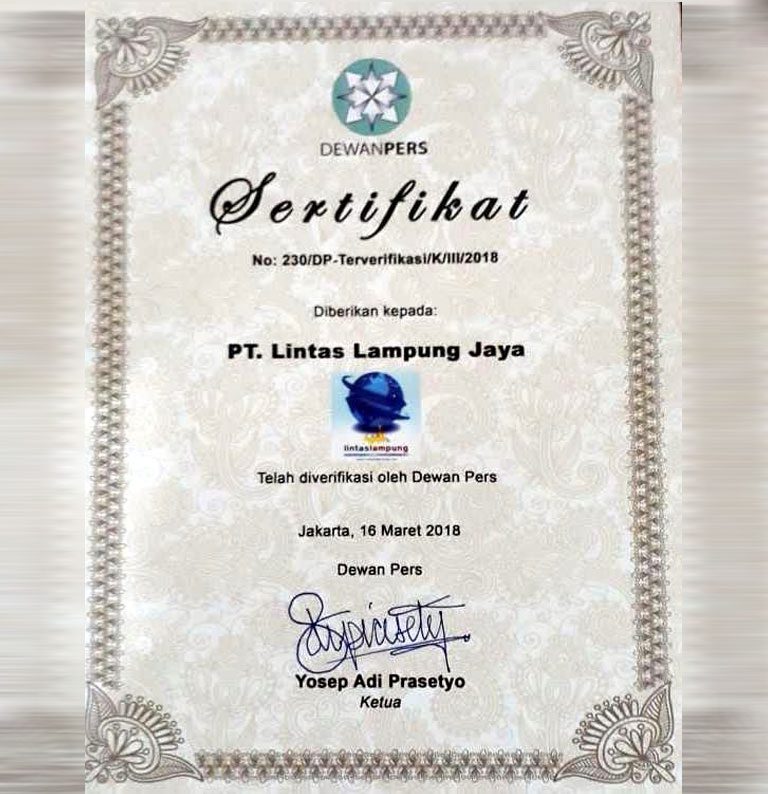Diki Danar Tri Winanti, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University;
Dosen Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Senang rasanya melihat kita dan masyarakat pada umumnya hari ini semakin sadar untuk menjaga konsumsi makanan yang sehat. Hal tersebut salah satunya berkat kemudahan akses informasi edukatif dari para pakar maupun pemengaruh (influencer) di berbagai platform media sosial. Di sisi lain, masyarakat juga mudah tersulut dengan konten-konten yang memasang judul bombastis namun ternyata isinya mengandung banyak ambiguitas data.
Contoh yang sempat viral satu bulan terakhir yaitu tentang kandungan susu UHT (ultra-high temperature) pada menu MBG (Makan Bergizi Gratis) yang hanya mengandung 30% susu sapi. Kegaduhan warganet tersebut memantik diskusi panjang menyangkut kelayakan susu “rekombinasi”. Hal ini menambah panjang polemik antara produk pangan ultra proses atau yang biasa disebut sebagai ultra processed food (UPF) yang diproduksi oleh industri besar atau manufaktur versus real food (makanan alami). Sekali saja sebuah produk menjadi konten negatif yang viral, maka yang terdampak langsung adalah reputasi perusahaan terkait. Jika kejadian semacam ini terus berulang, maka iklim investasi di Indonesia juga akan terdampak.
Yang perlu kita kritisi kemudian: apakah salah jika konsumen bersuara dalam rangka menuntut haknya untuk mendapatkan produk yang berkualitas? Dan apakah setiap perusahaan pangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak yang ditanggung konsumen?
Sebuah Paradoks
Pangan ultra proses (UPF) merupakan hasil dari rekayasa proses—baik dari persiapan bahan baku, proses pengolahan itu sendiri, hingga pengemasan dengan teknologi yang sesuai. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur simpan karena bahan pangan mudah rusak (shelf life), memudahkan konsumen menjangkau kebutuhan pangan yang bermutu secara terus menerus terutama untuk bahan-bahan yang sulit ditemukan di lingkungannya (affordability, convenience, sustainability), menyediakan pangan bergizi sesuai sifat alaminya maupun yang telah difortifikasi (nutrition value), serta mengenyangkan dan menyenangkan saat dikonsumsi (palatability).
Yang menjadi kontroversi di masyarakat adalah adanya stigma bahwa setiap produk UPF pasti tidak sehat. Hal ini muncul sejak adanya pernyataan dari seorang ahli gizi di Brasil bernama Monteiro dalam publikasi ilmiahnya pada tahun 2010. Ia menyebutkan bahwa kelompok ke-4 dari empat kelas produk pangan olahan yang diberi nama Klasifikasi NOVA—yaitu kelompok UPF—tidak sehat sehingga harus dihindari.
Konteks pernyataan Monteiro pada waktu itu adalah untuk memberi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Brasil yang sedang menghadapi tingginya angka obesitas dan diabetes akibat konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) yang berdampak pada penurunan produktivitas sumber daya manusia di negaranya. Monteiro menyebut industri makanan hanya mengedepankan kelezatan produk dan keuntungan semata tanpa memperhatikan dampak kesehatan konsumen.
Konsep “UPF tidak sehat” itu kemudian diamini oleh para ahli gizi dan dokter melalui penelitian dan edukasi ke masyarakat lokal hingga global. Di saat yang sama, para ilmuwan pangan dan pelaku industri mempertanyakan kesahihan pernyataan tersebut karena faktanya pangan olahan yang selama ini mereka pelajari dan produksi justru bertujuan untuk memudahkan konsumen mengakses produk pangan yang berkualitas. Para ahli pangan bersama para pemangku kepentingan banyak melakukan penelitian dan kajian kebijakan terkait dampak proses pengolahan pangan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus melindunginya dari risiko kesehatan lanjutan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa ada industri pangan yang kurang memperhatikan komposisi bahan, tahapan proses produksi, dan nilai gizi yang aman bagi konsumen. Namun kita tidak dapat menghakimi semua industri pangan seolah-olah berpikir sependek itu. Kembali lagi pada premis awal bahwa mutu produk adalah pertaruhan reputasi dunia industri di hadapan publik.
Paradigma Baru Konsumen
Berkaca dari polemik tersebut, hal positif yang dapat kita ambil hikmahnya adalah semakin sadarnya masyarakat terhadap apa yang mereka konsumsi dan bagaimana dampaknya bagi kesehatan di masa depan. Hal ini tentu harus disikapi dengan bijak oleh para produsen, ilmuwan, ahli gizi, dokter, edukator, pemengaruh, lembaga perlindungan konsumen, pemerintah, dan kita sendiri sebagai konsumen agar tidak terjadi sesat pikir dan kegaduhan berkelanjutan.
Satu hal yang perlu kita sadari terlebih dahulu adalah hakikat dari pangan itu sendiri, yaitu “no food, no life”. Artinya, kita tidak dapat bertahan hidup tanpa mengonsumsi produk pangan. Tinggal bagaimana kita memilih produk pangan yang memang sesuai dengan kebutuhan (biologis, psikologis, fisiologis, sensori) dan kondisi kesehatan (diet & kebutuhan khusus).
Kita juga harus memahami bahwa teknologi pengolahan pangan terus berkembang untuk mengoptimalkan nilai dari sumber daya alam dan kebermanfaatannya bagi umat manusia. Setiap teknologi baru tentu akan memicu kontroversi. Sebagai contoh, optimalisasi produksi pangan melalui teknologi penyuntingan gen yang dikenal sebagai GMO (Genetically Modified Organism) mendapat stigma negatif, padahal juga memberi manfaat bagi masyarakat dan memutar rantai ekonomi baru.
Setiap pengolahan dan pengelolaan yang tidak sesuai kaidah etik maupun etis tentu akan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, para produsen industri pangan harus berpedoman pada filosofi pengembangan produk, yaitu untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat atas pangan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tidak boleh hanya satu aspek kebutuhan saja yang dipenuhi sementara aspek lain diabaikan—misalnya hanya mengedepankan kelezatan dan penjualan, namun mengorbankan keamanan karena memicu gangguan kesehatan.
Better Processed Food
Konsep yang digaungkan oleh salah satu pakar teknologi pangan Indonesia, Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, dalam rubrik Opini Kompas pada Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober 2025 lalu, untuk menjawab paradigma baru konsumen tersebut adalah better processed food. Konsep ini mencoba menyadarkan semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan produk pangan yang sehat dan tetap berkualitas. Untuk mewujudkan hal ini, tentu dibutuhkan pendekatan dan kolaborasi transdisiplin agar tujuan bersama dapat tercapai secara terukur.
Pendekatan kearifan lokal perlu diadaptasi menjadi pedoman umum pola konsumsi yang tepat bagi masyarakat suatu daerah. Hal ini penting karena kondisi biologis dan fisiologis seseorang pada umumnya merupakan hasil tempaan pola konsumsi sehari-hari sesuai dengan sumber daya yang dapat diakses di lingkungannya. Jadi, masyarakat tidak perlu memaksakan pemenuhan kebutuhan gizi dari olahan ikan tuna apabila di daerahnya sulit didapatkan. Cukup dengan mengonsumsi produk pangan lain yang nilai gizinya setara sehingga tujuan kesehatannya tercapai.
Pendekatan STEM (sains, teknologi, engineering/teknik, matematika) dan hilirisasi riset pada sektor pangan yang sering dipromosikan oleh pemerintah perlu diarahkan ke produksi pangan yang baik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Regulasi pemerintah harus menggunakan seluruh sumber daya dan perangkatnya untuk melindungi hak kesehatan warga negara agar tidak terjadi kemunduran kualitas generasi berikutnya. BPOM, BPJPH, dan YLKI harus terus meningkatkan perannya dalam menjembatani itikad baik industri dalam memproduksi pangan olahan dengan keinginan konsumen yang ingin mendapatkan pangan olahan yang aman, nikmat, dan bergizi.
Edukasi terkait pangan olahan harus dilakukan secara terstruktur melalui unit pendidikan dasar agar masyarakat sadar dan rasional dalam mengonsumsi makanan sejak dini. Media sosial yang menjadi saluran alternatif edukasi juga dapat dioptimalkan dan dikawal karena dinamika di ruang publik maya sangat cepat dan berdampak sistemik. Akhir kata, makanan UPF belum tentu tidak sehat, dan makanan non-UPF belum tentu sehat. Semua yang sehat perlu dikonsumsi secukupnya karena yang berlebihan akan mubazir bahkan berdampak negatif pada diri sendiri. Semoga generasi Indonesia ke depan semakin sehat dan produktif, dimulai dari makanannya.
Penulis : Diki Danar Tri Winanti
Editor : Ahmad Novriwan
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.