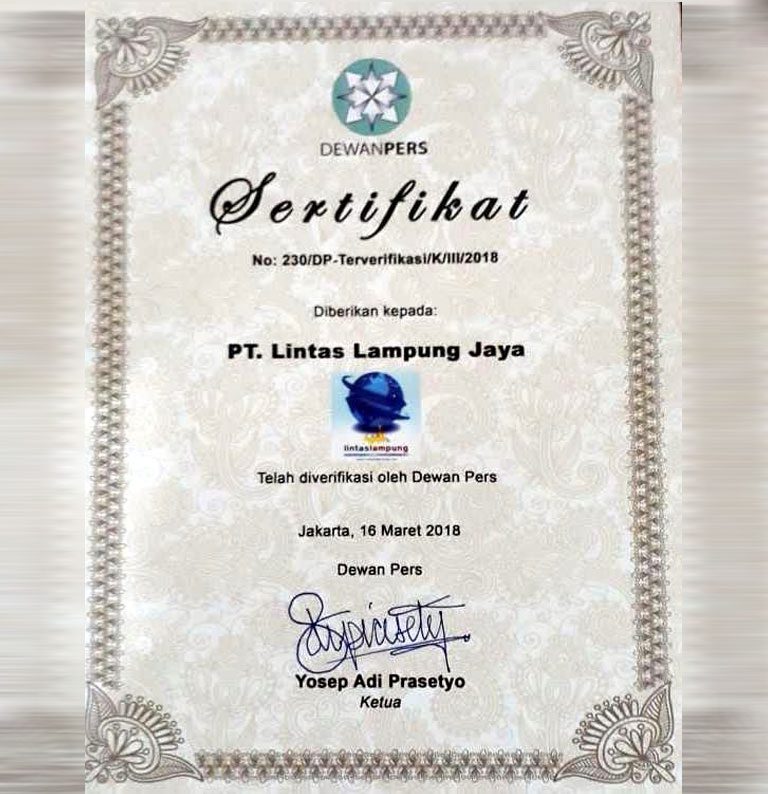Rudi Irawan, M. Pd, Dosen Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Megow Pak Tulangbawang
Dalam bayangan pandemic C-19, geliat modernisasi dan globalisasi di negeri ini terus bergulir mengiringi bangsa Indonesia dalam mengisi dan menghiasi kemerdekaan. Proses aktivitas manusia Indonesia modern di era globalisasi berbasis digital ini memberikan konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yakni adanya perubahan yang sangat berarti dalam jiwa zaman bangsa Indonesia dan tidak terlepas dari transformasi tata nilai bangsa tentang jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita hampir saja melupakan jati diri orang Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dengan peradaban dan kepribadian yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Perjuangan bangsa Indonesia dalam membangunkan nasionalisme dalam kesadaran bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa dan Negara ditandai dengan kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, Bangsa Indonesia bertekad mewujudkan cita-cita dan pencapaian tujuan nasionalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, suatu cita-cita yang menginginkan adanya kehidupan yang bebas bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. (Kemristekdikti, 2016). Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia bukanlah pemberian dari pemerintah kolonial Belanda atau Jepang, melainkan suatu Kemerdekaan Indonesia yang dicapai melalui perjuangan panjang bangsa Indonesia. Pada tahun 2022 ini, Republik Indonesia telah berusia 77 tahun sejak pertama kali diproklamirkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah pernyataan sakral dan berakarakter untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaaan UUD 1945, yaitu Indonesia yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bangsa Indonesia lahir dari perjuangan akan kesadaran bersama, semua suku bangsa yang mendiami nusantara yang merasa senasib dan sepenanggungan bergabung untuk menjadi suatu bangsa berdaulat dan berjuang bersama-sama, bahu-membahu merebut kembali kemerdekaannya dari kaum penjajah. Kesadaran inilah yang menghasilkan rasa nasionalisme bagi seluruh rakyat yang merasa dirinya tinggal dan hidup di Kepulauan Nusantara untuk menjaga, mempertahankan negeri ini dari segala macam penjajahan, baik yang berasal dari luar Negara Indonesia maupun yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri.
Kita memahami bahwa nasionalisme Indonesia lahir dari segala bentuk penjajahan atas bangsa dan negeri ini yang telah membuat penderitaan dan kesesengsaraan di berbagai bidang kehidupan rakyat, seperti Pertama. Bidang politik didominasi oleh pemerintahan asing dan hegemoni pemerintahan asing, sehingga bangsa ini tidak berdaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam untuk menciptakan kemakmuran di berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu nasionalisme Indonesia di bidang politik bertujuan menghilangkan dominasi politik negara asing dengan membentuk pemerintahan berkedaulatan rakyat. Kedua. Eksploitasi ekonomi. Setiap pemerintahan kolonial berusaha mengeksplotasi sumber alam negeri yang dijajahnya untuk kemakmuran dirinya, bukan untuk kemakmuran negeri jajahan. Rakyat juga diperas dan dipaksa bekerja untuk kepentingan ekonomi kolonial, misalnya seperti terlihat kerja Rodi pada masa Herman William Daendlles atas nama pemerintah sementara kekuasaan Perancis di Hindia Belanda, dominasi dan monopoli pihak kolonial dibidang ekonomi dan politik atas negara-negara (kerajaan) yang ada di Indonesia, sistem tanam paksa (culturstelsel) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda di Jawa pada awal abad ke-19 dan menimbulkan berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia, seperti Perang Diponegoro, perang Aceh, Perang Raden Intan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, nasionalisme Indonesia hadir pada waktu itu adalah untuk menghentikan segala eksploitasi ekonomi dan politik asing dengan pola kemandirian dan berdikari. Ketiga. Penetrasi budaya. Kolonialisme juga secara sistematis menghapuskan jati diri suatu bangsa dengan menghancurkan kebudayaan dan budaya bangsa yang dijajahnya, termasuk agama yang dianutnya. Caranya dengan melakukan penetrasi budaya, terutama melalui sistem pendidikan, sosial dan politik. Karena itu di bidang kebudayaan, nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan integritas dan perkembangan jiwa zaman generasi bangsa. Dalam artian, Ia tidak menolak dampak dan pengaruh kebudayaan luar yang merupakan konsekuensi dari kolonisasi, modernisasi dan globalisasi, tetapi menyaring dan menyesuaikannya dengan pandangan hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (worldview, Weltanschauung) bangsa Indonesia.
Proses terbentuknya kesadaran nasionalisme untuk menjadi satu bangsa yang berdaulat telah tumbuh dan berkembang dalam waktu ratusan tahun, terutama sejak kaum kolonial Belanda menjajah Nusantara. Baru pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai suku bangsa yang mendiami Nusantara mengucapkan Sumpah Pemuda : satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dalam sejarah bangsa; Sumpah Pemuda adalah satu hal, namun hal lain yang tak kalah pentingnya adalah substansi dan hakikatnya. Kekhawatiran akan semakin lunturnya kecintaan terhadap kebangsaan dan ke Indonesiaan di kalangan masyarakat kita sekarang, bisa jadi merupakan peringatan awal dari kecenderungan yang menafikan perjuangan para pendahulu dalam menyusun sebuah republik yang diberi nama Indonesia. Apalagi bila ukuran ini dipadankan dengan bagaimana sebagian dari kita sekarang memahami budaya sendiri dibandingkan dengan mencangkok gaya hidup cosmopolitan, seperti K Pop, gaya muda-mudi di jalan Citayem (trend Citayem), dan gaya liberalisasi yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia, maka akan semakin pesimis pula di dalam memandang kualitas wawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an sekarang. Apalagi dengan makin gencarnya penguasaan asing atas aset-aset ekonomi dan sumber daya alam kita, sangat beralasan bila kemudian muncul kepedulian untuk mengaktualkan persoalan ini. Oleh karena itu, salah satu kepedulian bangsa dalam meningkatkan kesadaran akan pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi generasi bangsa saat ini merupakan tonggak penting yang menandakan telah tergemblengnya suatu kesadaran, kesepakatan dan tekad berbagai suku bangsa yang mendiami Nusantara untuk bergabung bersatu menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kesadaran sebagai satu bangsa itulah yang melahirkan ideologi Nasionalisme Indonesia yang makin lama makin kuat dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Untuk menghadapi politik pecah-belah kaum penjajah Belanda, para pemimpin pejuang kemerdekaan Indonesia, terutama para founding fathers bangsa Indonesia Bung Karno, Bung Hatta, K.H. Agus Salim, M. Natsir, dan Muh. Yamin berusaha mempersatukan segenap komponen bangsa di bawah bimbingan ideologi Nasionalisme Indonesia tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dicapai, terutama dengan senjata “persatuan bangsa Indonesia dibawah bimbingan ideologi Nasionalisme Indonesia”.
Baik dilihat dari proses kelahirannya maupun dari isinya, ideologi Nasionalisme Indonesia adalah sebuah ideologi maju yang mempunyai tiga tujuan. Pertama: agar bangsa Indonesia dapat mencapai kemerdekaannya dari penjajahan kaum kolonial Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, Jepang dan dari penguasaan kaum neo-kolonial sesudahnya, baik itu dari internal maupun eksternal sehingga menjadi suatu bangsa yang “merdeka dan berdaulat”. Kedua, agar bangsa Indonesia dapat membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur di tanah air di atas kemandirian bangsa Indonesia. Dan ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketiga tujuan mulia ini tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Menghadapi hujatan para pendukung ideologi neo-liberal yang menganggap ideologi nasionalisme telah “ketinggalan zaman”, “tidak sesuai dengan proses globalisasi”, kita ingin mengajukan pertanyaan di bawah ini. Apakah salah bila bangsa Indonesia berjuang menentang kolonialisme dan neo-kolonialisme demi merebut kembali kemerdekaan dan kedaulatannya? Apakah salah bila kemerdekaan dan kedaulatan tersebut digunakan oleh bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat Indonesia dalam mencapai keadilan dan kemakmuran di tanah air Indonesia ? Apakah salah, bila bangsa Indonesia yang menjadi bagian dari bangsa-bangsa di dunia ini ikut serta membangun ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ? Disadari atau tidak oleh para “internasionalis”,para “metropolitanis”, dan para “globalis” tersebut, hujatan terhadap Nasionalisme Indonesia secara objektif telah berperan melapangkan jalan bagi ekploitasi kaum kapital global terhadap sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia bangsa Indonesia. Keterpurukan Indonesia dewasa ini adalah akibat melaksanakan politik ekonomi neo-liberal yang dipaksanakan oleh lembaga-lembaga keuangan Internasional kepada Indonesia. Ini nyata-nyata bertentangan dengan dasar-dasar politik ekonomi nasional ? Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ini berarti bahwa kekayaan alam Indonesia harus dijadikan modal dasar bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Sekarang kita menyaksikan bagaimana di bawah arahan politik ekonomi neo-liberal yang dijalankan pemerintah kita, dari hari kehari kekayaan alam bangsa Indonesia berpindah tangan kepada kaum kapital global ! Menjalankan terus politik ekonomi neo-liberal berarti mempercepat pengalihan asset-asset bangsa Indonesia ketangan kaum kapital global. Berarti sadar atau tidak, bertindak mengutamakan kepentingan kaum neo kolonialisme dengan bajunya yang kapitalis, liberalis dan globalis adalah tindakan yang memiskinkan bangsa Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia sebagai koeli/jongos di negeri sendiri dan bangsa koeli/jongos di antara bangsa-bangsa di dunia ! Apakah kita akan membiarkan proses “kolonialisasi” bangsa Indonesia berjalan terus ?
Tak ada yang dapat kita harapkan dari ideologi neo kolonial dan neo-liberal selain proses pemiskinan dan ketidakberdayaan bangsa Indonesia. Seperti ditunjukkan oleh pasal 33 UUD 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita perlu merebut kembali penguasaan terhadap kekayaan alam milik bangsa Indonesia yang sekarang ini banyak dikuasai oleh kaum kapital global. Sebagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia, perjuangan merebut kembali kekayaan alam milik bangsa Indonesia baik yang berada di daratan maupun di lautan tanah air kepulauan Indonesia hanya mungkin dicapai dengan “persatuan bangsa di bawah bimbingan ideologi Nasionalisme Indonesia”. Kepemilikan, kebermanfaatan dan pemberdayaan atas sumber-sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia adalah modal dasar bagi bangsa Indonesia untuk keluar dari keterpurukan dewasa ini dan bangkit dalam kemandirian kesejahteraan guna mewujudkan keadilan dan kemakmuran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Itulah yang dimaksud dengan hakekat kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia saat ini dengan segala pernak-perniknya.
Masih segar dalam ingatan kita tentang nasionalisme bangsa ini di era perang kemerdekaan dan masa-masa awal republik ini lahir, wawasan kebangsaan (nationness) dan ke Indonesiaan diwujudkan oleh para pendiri republik dalam bentuk perang melawan penjajah (asing). Apakah Portugis, Belanda, Perancis Inggris atau pun Jepang, akan dianggap sebagai musuh bersama bila negara-negara kolonial itu berusaha kembali menguasai tanah air Indonesia. Hanya dengan modal wawasan kebangsaan itulah Indonesia bisa dipersatukan. Dengan itu pula Indonesia lahir menjadi sebuah Negara Baru (New Emerging Forces-Nefos) yang ingin dihargai sederajat dengan Negara-Negara Lama (Old Emerging Forces-Oldefos) yang sebelumnya menguasai seluruh jagat ini. Sampai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno, relevansi pengaktualan wawasan kebangsaan dan ke Indonesiaan masih sering dimunculkan dalam semangat “nation and character building”, yang anti asing, terutama negara bekas penjajah dengan segala macam antek-anteknya. Ungkapan Presiden Soekarno yang sangat terkenal “go to hell with your aid” menjadi bukti abadi dari betapa jelasnya pilihan politik luar negeri Indonesia saat itu. Bantuan dari negara mana pun ditolaknya bila harus ditukar dengan pendiktean mereka terhadap Indonesia.
Pikiran baru mengenai nasionalisme di atas mengindikasikan bahwa monopoli interpretasi dan sentralisasi pengertian tentang nasionalisme harus digantikan oleh demokratisasi pemahaman secara lebih substansial. Karena nasionalisme adalah “komunitas politik yang dibayangkan” (imagined political communities), maka perlu ada sharing of ideas dan bahkan socio-political sharing antar berbagai masyarakat pendukungnya (fellow-members). Tanpa itu semua, jangan heran bila eksistensi nasionalisme akan terganggu, dan pada gilirannya “temuan” (invent) itu akan hilang. Apalagi untuk negara bangsa sebesar dan sekompleks Indonesia sekarang, “justice sharing” (pembagian yang berkeadilan) antara berbagai elemen bangsa dan daerah menjadi sebuah keharusan. Karena kemajemukan (bhineka) menjadi dasar dari kesatuan (Ika), menjadi mutlak sifatnya bagi siapa pun untuk memberi perhatian kepada keadilan, baik dalam bentuk maupun substansinya antar golongan, antar agama, antar suku, antar wilayah, antar gender, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, nasionalisme Indonesia hanya dapat dikontekstualkan, apabila kita semua memperhatikan peran berbagai nilai-nilai lokal di dalamnya. Dengan mempercayai (trust) peran nilai-nilai lokal tersebut, berarti kita telah menemukan kembali “modal sosial” (social capital) yang menjadikan negara bangsa ini lahir dan terus bertahan sampai sekarang.
Nasionalisme Semu Bangsa Indonesia Sebuah Tantangan
Kini, ketika konsep pembangunan mulai mengalami banyak distorsi dalam praktiknya, dan Perang Dingin tidak lagi mewarnai politik internasional, bagaimana kita hendak mengaktualkan wawasan kebangsaan dan ke Indonesiaan di atas. Masalahnya, banyak di antara kita yang sering terkaget-kaget dengan perkembangan mutakhir yang nampaknya lebih memperkuat globalisme ketimbang nasionalisme. Sampai-sampai ada tulisan Jakob Soemardjo, seorang sastrawan senior yang merasa khawatir, jangan-jangan Sumpah Pemuda kita sekarang adalah “Dunia tanah airku, kemanusiaan adalah kebangsaanku, dan Bahasa Inggris adalah bahasaku”.
Hal ini ditunjukkan dengan gejala- gejala yang muncul dalam kehidupan sehari- hari anak muda sekarang, misalnya dilihat dari cara berpakaian, banyak remaja- remaja kita yang berdandan seperti selebritis yang cenderung ke budaya Barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim dengan memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan. Pada hal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan kita. Tak ketinggalan gaya rambut mereka yang dicat beraneka warna. Pendek kata orang lebih suka jika menjadi orang lain dengan cara menutupi identitasnya, ketimbang menjadi diri sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian dan berpedoman pada nilai-nilai budaya Timur. Di sisi lain, perkembangan dan kemajuan teknologi internet memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses oleh siapa saja. Apa lagi bagi anak muda, internet sudah menjadi bagian/santapan sehari-hari. Jika digunakan secara semestinya tentu kita memperoleh manfaat yang berguna, tetapi jika tidak, kita akan mendapat kerugian. Dan sekarang ini, banyak pelajar dan mahasiswa yang menggunakan tidak semestinya, misal untuk membuka situs-situs porno dan situs-stus yang sifatnya tidak mendidikan bagi kehidupan anak bangsa. Bukan hanya internet saja, ada lagi pegangan wajib mereka yaitu handphone. Rasa sosial terhadap masyarakat menjadi tidak ada karena mereka lebih memilih sibuk dengan menggunakan handphone.
Dilihat dari sikap, banyak anak muda yang tingkah lakunya tidak kenal sopan santun dan cenderung cuek tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan, menimbulkan paradigma yang meniadakan pentingnya “nation building”. Tentu saja hal ini tidak keliru dari perspektif teoritik dan apalagi praksis-pragmatik. Namun tidak boleh juga dianggap sebagai memiliki kebenaran mutlak. Sebagaimana tradisi yang berlaku dalam masyarakat akademik, apa yang disebut contending theory atau teori tandingan, mesti dianggap sebagai sebuah keniscayaan. Dalam konteks bangsa dan wawasan kebangsaan inilah, kita dihadapkan pada dua tantangan paradigma utama yang masing-masing memiliki landasan empirik yang cukup kuat. Pertama, paradigm Perennialism (nation building) yang lebih menekankan pada komunitas budaya, immemorial, berakar, organik, kualitas, kerakyatan dan turun temurun (ancestrally-based). Kedua, teori Modernism. Perspektif ini lebih menekankan pada komunitas politik, modern, diciptakan, mekanistik, terbagi, sumber daya, konstruksi elit dan basisnya komunikasi. Kedua, secara empirik, Indonesia kontemporer adalah Indonesia yang tidak mungkin lagi dapat membebaskan dirinya dari pengaruh globalisme. Suka atau tidak, karena begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tidak ada bagian dari wilayah Republik Indonesia yang tidak tersentuh olehnya. Sejak diperkenalkannya jaringan sistem komunikasi satelit domestik (SKSD) pada akhir dasawarsa 1970-an, hubungan antar wilayah lewat jaringan tersebut kian dipermudah. Memasuki dasawarsa 1990-an dan sesudahnya, tingkat kemudahan berkomunikasi semakin dirasakan secara signifikan. Bukan hanya antar kota besar, melainkan juga sampai ke pelosok-pelosok wilayah terpencil di seluruh Indonesia, telah dihubungkan oleh berbagai penyedia jaringan telepon. Dari waktu ke waktu, kecepatan dan kualitas berkomunikasi semakin ditingkatkan. Operator telepon nirkabel, sudah bukan lagi menjadi mimpi masyarakat di pedesaan. Bila sampai dengan 1980-an, untuk mendapatkan sambungan telepon dengan kualitas yang baik saja masih sulit, sekarang di tahun 2012, asal ada uang, siapa pun dapat mengakses dan menggunakan telepon seluler dan internet secara bebas dan menjadi raja di negeri ini.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah menjadi bagian dari pasar global. Bersamaan dengan tingkat kemajuan di dunia komunikasi tersebut di atas, pasar pun tidak lagi mengenal batas-batas ideologis dan wilayah secara jelas. Apalagi setelah Perang Dingin berakhir, dan Kubu Komunis tidak lagi menjadi penghambat Kubu Kapitalis, maka bahasa dan logika pasarlah yang menentukan peradaban dunia sekarang. Ditambah dengan makin mudahnya sarana transportasi, maka jarak bukan lagi faktor krusial sekarang. Konsep “pembeli adalah raja”, dewasa ini telah digantikan oleh “penjaja adalah raja”. Kedaulatan konsumen yang merupakan salah satu norma yang diyakini para ekonom murni di masa lalu, sekarang tidak terlalu mudah untuk dikenali. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, penjaja mampu menentukan selera konsumen. Bahkan lebih dari itu, negara pun kian berkurang perannya dibandingkan para aktor ekonomi pasar sekarang. Karena diberlakukannya berbagai ketentuan rezim internasional dan rezim pasar bebas, maka intervensi politik dalam mekanisme pasar sungguh-sungguh dijauhi. Lebih tragis lagi adalah bahwa pasar, dengan segala macam keunggulannya, dan sistem kapitalistik dengan berbagai kelebihannya, belakangan telah menjadi penentu utama politik internasional. Karena tiadanya pelaku pasar lain yang kuat, ekonomi pasar telah benar-benar menguasai jagad raya sekarang. Negara dan aturan yang sebelumnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sekarang digantikan oleh berbagai idiom yang merepresentasikan pasar. Sumber nilai masyarakat sebagian besar juga berasal dari sana. Uang dan kepuasan menjadi nyawa baru kehidupan abad ini. Berbagai norma dan ideologi lain yang kurang konkrit, menjadi norma yang makin obsolete, dan kemudian ditinggalkan penganutnya. Termasuk konsep nation and nationality, atau nationness, menghadapi tantangan yang tidak kecil.
Karena pemikiran dan praksis seperti dikemukakan di atas, maka sungguh layak bila kita kemudian mempersoalkan kemerdekaan dan nasionalisme di negeri ini. Betapa tidak, bila di masa lalu, pemerintah masih sangat berperanan dalam proses pembentukan negara ini, sekarang, pemerintah dihadapkan pada berbagai kesulitan. Pertama, sumber daya politik dan ekonomi pemerintah sendiri makin lama makin berkurang. Pemerintah kian menghadapi kesulitan untuk memobilisasi dukungan masyarakat karena terjadinya ketimpangan antara kemampuan dengan tuntutan publik. Sesuai dengan ideologi ekonomi kita, pemerintah mestinya mampu menjadi sebuah lembaga yang mengatur kesejahteraan sosial. Namun dalam kenyataannya, terutama sejak krisis moneter pertengahan 1990-an sampai sekarang, pemerintah semakin tidak berdaya menghadapi tuntutan pembangunan. Bila di masa lalu pemerintah banyak mensubsidi masyarakat, sekarang sebaliknya, masyarakatlah yang harus melakukannya. Kedua, lemahnya sumber daya pemerintah untuk merespon harapan masyarakat dipersulit oleh makin kompleksnya tantangan yang dihadapi pemerintah sekarang. Proses demokratisasi yang memakan waktu dan mahal, telah menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan proses politik ini ketimbang proses-proses non-politik. Mulai dari pengembangan peran serta masyarakat, pelembagaan organisasi, pemilihan umum sampai dengan proses lobby-lobby politik, semuanya memerlukan anggaran yang tidak kecil. Tragisnya lagi, korupsi pun bukannya semakin berkurang dengan adanya pengawasan independen, justru sebaliknya. Sampai tulisan ini dibuat, posisi Indonesia dalam bidang yang satu ini, masih tetap menduduki kelompok lima besar dunia. Ditambah lagi dengan tragedi bencana alam yang datang silih berganti, semuanya memerlukan dana publik yang juga tidak sedikit. Sebagai akibatnya, harapan masyarakat luas untuk mendapat santunan pemerintah kian sulit direalisasi. Pada gilirannya, para elit politik menikmati hasil reformasi, sementara masyarakat luas kian jauh dari pelayanan. Tidak terlalu mengherankan bila kemudian kepercayaan masyarakat baik terhadap hukum dan lembaga negara semakin menyusut. Ketiga, globalisasi ekonomi telah berdampak luas terhadap perubahan ekonomi di dalam negeri. Meski pun pemerintah tetap berusaha untuk menjalankan perannya, pengaruhnya kian terpinggirkan oleh keniscayaan nilai yang dibawa bersamaan dengan masuknya pasar bebas dalam kehidupan masyarakat kita. Bila di masa lalu, negara masih memiliki monopoli dan pengaruh yang kuat dalam menentukan perubahan masyarakat, sekarang tidak lagi. Orientasi pada pasar, telah melahirkan persaingan secara bebas, yang akhirnya si besar makan si kecil, privatisasi Badan Usaha Milik Negara telah menghilangkan otoritas pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan warganya. Karena reformasi pula maka tatanan hukum yang dianggap sudah mapan selama ini, menjadi goyah. Munculnya interpretasi hukum secara kontekstual, telah menjungkir-balikkan norma lama yang dianggap tidak lagi menzaman. Karena ketentuan perundangan yang baru belum ada, sementara aturan yang lama ditolak, kepastian hukum menjadi sebuah komoditas yang amat langka. Akibatnya, interpretasi sepihak telah menjadi sebuah instrumen perubahan. Pada gilirannya, kebimbangan terlihat jauh lebih menonjol ketimbang kepastian hukum.
Kesemua kecenderungan dan fenomena mutakhir di atas, tentu akan merugikan teraktualisasikannya wawasan kebangsaan dan ke Indonesiaan sebagaimana seharusnya menjadi modal politik dan moral sebuah negara bangsa. Sebab, sebagai sebuah masyarakat politik (political community), Indonesia kapan pun membutuhkan adanya kesamaan persepsi dan cita-cita antara elit dengan massanya, antara pemerintah dengan kekuatan non-pemerintah, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai elemen negara bangsa yang lain. Tidak boleh ada yang menjadi korban darinya. Ketika rakyat masih terbatas pengetahuan dan kesempatannya, mungkin pilihan untuk mencari sistem nilai ataupun contoh perilaku (role model) yang lain masih terbatas. Mereka bisa saja menjadi kekuatan mayoritas diam (silent majority), yang seolah-olah pasif dan bahkan “manut” (tunduk pada pemimpin). Tapi sekarang lain. Di era dunia tanpa batas, berbagai sumber perubahan dapat diperoleh dari berbagai penjuru dunia, terutama pasar dan pengalaman negara-negara lain. Agar iklim politik yang tidak kondusif terhadap perwujudan cita-cita mulia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak berlarut-larut, ada beberapa pemikiran yang perlu ditawarkan dalam kesempatan ini:
- pemerintah secara terus-menerus menunjukkan komitmennya terhadap upaya perbaikan bangsa. Kalau pun sampai sekarang masih bersikap reaktif, dan belum didasarkan pada visi, dan bahkan rencana tindakan yang jelas, dalam jangka pendek ke depan, pemerintah harus segera merevisi pendekatan yang “tidak mau ambil resiko ini”. Rakyat kebanyakan sebenarnya akan dapat bersabar dan mau mendukung pemerintah bila pemerintah pun konsisten di dalam melaksanakan fungsinya. Transparansi persoalan publik telah mendidik rakyat, dan karenanya mereka akan dapat mengerti bahwa persoalan yang dihadapi negara-bangsa ini sangat kompleks. Dengan kata lain, kejujuran, konsistensi, Integritas dan kemauan kerja pemerintah yang cukup keras akan dapat mengamankan proses transisi yang sedang kita jalani sekarang.
- pemerintah dan para elit politik harus mulai melakukan perubahan tingkah laku (behavioral changes). Terutama dalam kaitannya dengan gaya hidup masing-masing pejabat tinggi. Mulai dari presiden sampai ke anggota kabinetnya, pimpinan partai politik dan tokoh panutan masyarakat lainnya, perlu meneladani sebuah cara memerintah yang empati terhadap krisis dan nasib masyarakat kebanyakan. Pendekatan elitis harus disingkirkan, bukan hanya sekedar pidato atau menjalankan berbagai acara yang seolah bernuansa populis, namun melaksanakannya secara sistemik dan melembaga. Aturan baru dibuat dan dilaksanakan, sehingga akan dijadikan pegangan semua pihak dalam masa-masa selanjutnya. Depersonalisasi kekuasaan harus menjadi semangat para penyelengara negara dalam mengembangkan berbagai kebijakan publik
- pemerintah tidak melihat persoalan ekonomi bangsa ini dari sekedar kacamata ekonomi murni. Bila kekurangan anggaran selalu dikompensasi dengan pengurangan subsidi, peningkatan dan penambahan objek pajak diberbagai bidang kehidupan, serta penambahan hutang negara dengan kepada negara lain atau donator internasional, di sisi lain penegakan hukum masih sangat memprihatinkan dengan corak keadilannya dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya. Hal tersebut akan membuat masyarakat paling bawah akan terus menderita dan tidak memiliki akses hidup untuk kesejahteraan dan kemakmuran, serta pengakuan diri di khalayak umum. Dan ini sangat potensial untuk membangkitkan radikalisasi massa. Bagi mereka yang ingin menggunakan kesempatan di balik kesempitan, jelas mendapat keuntungan untuk membalikkan keadaan, dengan mengatakan bahwa pemerintah tidak well performed. Pemerintah mesti menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya, perlu segera diadakan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dan di mulai dari ring satu, seperti keprisedenan, kementrian, kepolisian, parlemen, dan kejaksaan. Dalam menghadapi berbagai kesulitan anggaran, pemerintah mesti menjadi pionir untuk menerapkan apa yang dikatakan sebagai “anggaran berbasis kinerja” (money follows function). Pemangkasan lembaga negara yang tidak diperlukan, menjadi agenda utama pemerintah. Semangat ini pun mesti ditiru oleh Lembaga Perwakilan Rakyat kita. Ketika sumber dana pembangunan makin berkurang, DPR harus menjadi contoh untuk melakukan penghematan, bukan mendemonstrasikan kekuasaan. Struktur lembaga ini mesti dirampingkan, dan kinerjanya ditingkatkan. Orientasi pada “bagi-bagi kekuasaan” harus ditinggalkan. Untuk apa struktur kepemimpinan MPR masih dipertahankan seperti sekarang. Melihat beban kerja MPR dewasa ini, rasanya negara terlalu mahal untuk membayarnya.
- pendekatan yang sifatnya “Jakarta Sentris” (Centered Bias) harus dipadukan dengan pendekatan yang memperhatikan kepentingan lokal serta masyarakat. Demokratisasi meniscayakan hilangnya monopoli penafsiran dan kekuasaan. Keadilan dan pembagian (sharing) antar komponen bangsa di seluruh Indonesia harus dijadikan paradigma utama dalam mempertahankan eksistensi nasionalisme ke Indonesiaan yang menghargai ke-Bhinneka-an dan ke-Tunggal Ika-an. Dengan kata lain, krisis kepercayaan (crisis of trust) antara elit dengan massa, intra pemerintah sendiri, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara negara dan masyarakat, antara partai politik dengan civil society, antara pengusaha dengan buruh, serta intra masyarakat itu sendiri, mesti dihilangkan.
Memang tidak keliru bila di dalam menilai politik Negara Indonesia, kita selalu berpegang pada keberadaan dan nasib seorang presiden beserta jajaran pemerintahannya. Karena latar belakang kita yang sangat state centered dan bureaucratic state, maka gonjang-ganjing politik senantiasa dimulai dari sana. Betapa besarnya peran negara dalam mengarahkan perubahan sosial, serta kekayaan yang dimilikinya untuk menjalankan fungsi tersebut, negara, khususnya pemerintah masih tetap menjadi wilayah yang paling menarik banyak pihak. Perlombaan untuk memperoleh akses ke dalamnya nampaknya masih tetap berlangsung. Tidak terlalu mengherankan bila sekarang mulai berkembang berbagai manuver politik dari sementara tokoh “tua” dan “generasi muda” yang mempersoalkan suksesi kepemimpinan pada 2024 mendatang. Ada keengganan untuk berestafet politik, di satu pihak, juga ada kecurigaan pelanggengan kekuasaan dengan isu-isu tiga periode di pihak lain. Padahal masalah kemerdekaan dan kedaulatan dalam pengelolaan negara dan bangsa sekarang sudah jauh dari itu. Nasionalisme dalam kehidupan kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini adalah mengamalkan moralitas, integritas dan kejujuran dalam menciptakan good government guna memakmurkan rakyat Indonesia di berbagai bidang kehidupan. (*)
*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.